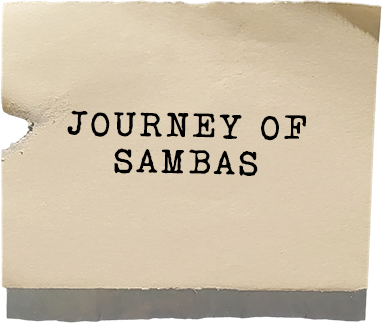
-
Jubata-Jubata.
Kami datang dari jauh, dan tak pernah terang.
Di atas laut, kapal kami membelah Laut Jawa 32 jam.
Matahari datang dan tenggelam berganti. -
Di lambungnya, kami berdiri.
Ratusan mata menuju kami.
Kulihat rindu, harapan berserak, kepulangan dan kepergian niscaya.
Atau pelarian terbaik. -
Kami menjadi asing, atas diri.
Siapakah sebenarnya diri kami?
-
Sampailah kami di dermaga Pontianak, selepas malam pada suatu pagi membawa kami kepada Singkawang.
Disini, puluhan potrait masa silam pernah terekam di ingatan, tentang tapal batas antara kematian dan hidup. -
Inilah ruang liminal, ruang diantara, yang ambang dan menegas.
Kilometer jarak telah kita tempuh, dari nyala matahari dan lampu jalanan berlalu. -
Kami berdiri, menunggu rumah di pundak kami di datangi.
Kemarilah, siapapun bisa menghuni. -
Laut Sentete, disini di penghujung sungai, tempat air mengalir sampai jauh.
Bertahun silam dalam gelap perahu melaju, membawa ibu dan anak-anak. -
Ada seseorang bernama Ali menepati janji.
Dan ia tak pernah pergi.
Ibu dan anak selamat dalam gelap.
-
Perahu kami berjalan mundur, memecah sungai sungai.
Kulihat masa lalu berlalu.
Merekam lanskap kota dalam ketiadaan. -
Ada yang sublim, dan tak terkatakan.
Aku datang kedua kalinya ke kota ini, dengan perasaan yang tak sama. -
Perahu ini melaju, semakin jauh, membelah kota.
Membelah sejarah yang gelap dan anyir. -
Disini, aku melihatnya.
Bersama Aloysius hantu itu semakin samar. -
Seperti bayang...
-
Katakan pada kami, hantu hantu itu hanya bayang.
Dengan nyala cahaya kita akan membunuhnya. -
Perjalanan ini sampai pada ujung jaraknya.
Aruk... tapal batas negara membangun utopianya.
Untuk hidup dalam damai. -
Tapi saling bunuh, tapi saling bunuh, dan terus berulang.
-
Pohon tua menatap kami, ia menunggu.
-
Sama sepertiku, sama seperti Aloysius.
Kami menunggu rumah di pundak kami di huni.
Siapapun bisa memasukinya.
Siapapun bisa menghuninya. -
Kemarilah...














